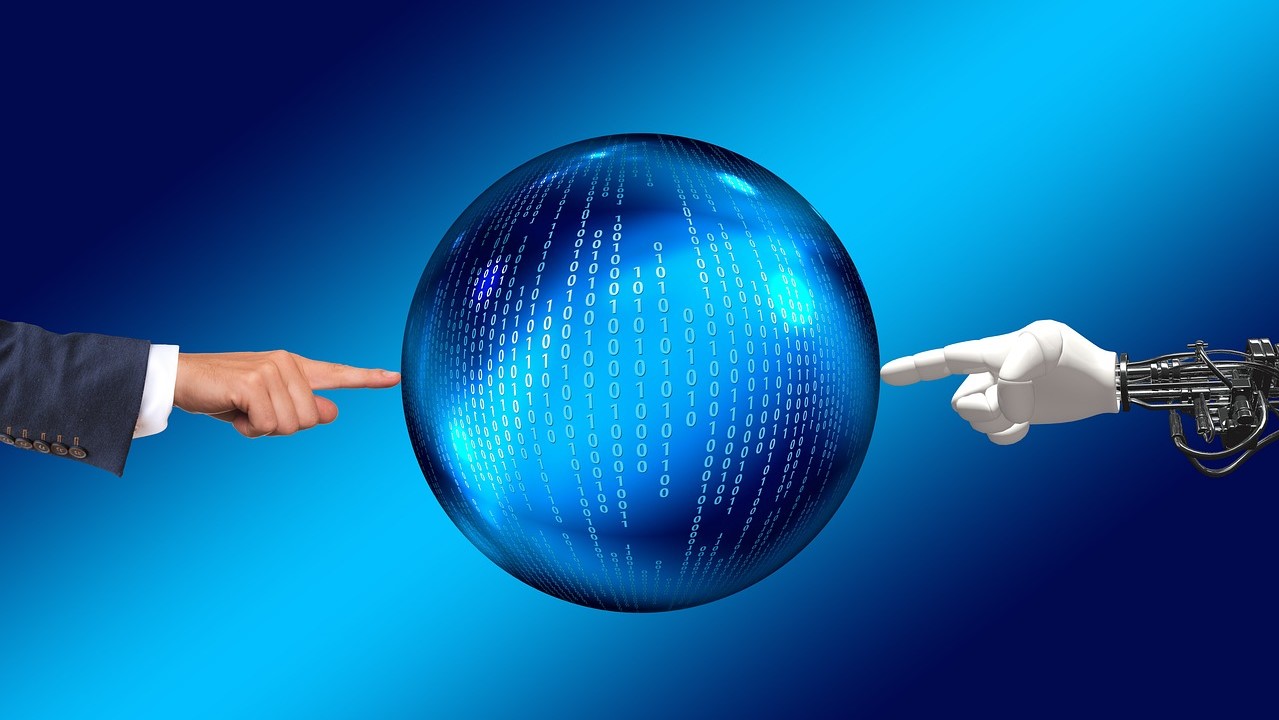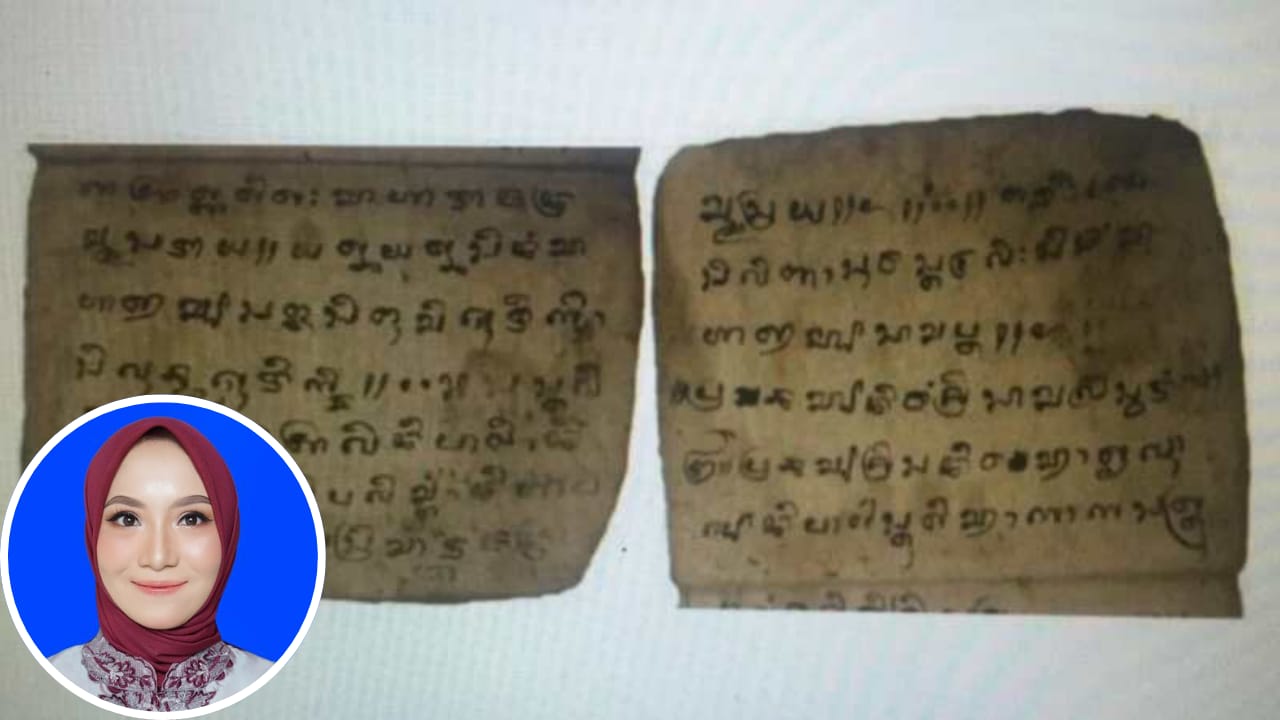Oleh: Fauzul Ikhsan Dafiq
Beberapa tahun terakhir, fenomena judi online di Indonesia terasa semakin mengkhawatirkan. Tak lagi hanya menjadi "rahasia umum" di kalangan dewasa, kini virusnya telah menjangkiti remaja bahkan anak-anak. Coba buka media sosial atau scroll beberapa grup obrolan dengan mudah kita temukan tautan menuju situs-situs permainan slot, taruhan bola, roulette, dan sejenisnya. Semua itu dikemas rapi, penuh warna, dan tampak "aman", padahal sebenarnya adalah jebakan.
Judi online telah menyelinap ke dalam ruang privat masyarakat, menyaru sebagai hiburan digital. Ini membuat kita bertanya, apakah ini semata kelalaian pemerintah yang lalai menjaga gerbang digital, atau memang kesalahan sosial yang didiamkan hingga menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging?
Di antara lompatan teknologi dan celah regulasi, kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman telah berubah. Internet cepat dan smartphone murah menjadikan hampir semua orang dari kota hingga pelosok desa terhubung ke dunia maya. Sebagaimana yang saya kutip dari laporan APJII (2024), pengguna internet di Indonesia telah menembus angka 220 juta. Ini angka yang luar biasa, sekaligus jadi peluang emas bagi para pelaku bisnis ilegal, termasuk judi online.
Padahal secara hukum, negara jelas melarang perjudian. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elekrotnik, ada KUHP Pasal 303 tentang perjudian, dan ada pula aturan pelengkap lainnya. Tapi, mengapa masih banyak situs judi yang berkeliaran bebas, bahkan muncul kembali dengan nama baru hanya beberapa jam setelah diblokir?
Fakta ini menyiratkan satu hal yaitu pemerintah lambat, atau mungkin bahkan lengah. Sebagaimana dalam laporan Kominfo tahun 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 800.000 situs judi telah diblokir. Tapi jujur saja, pemblokiran ini seperti menambal timba bocor yang berisi air dengan tisu yang mana tak akan bertahan lama. Kita harus menyadari bahwa teknologi mereka lebih cepat dari langkah birokrasi kita.
Antara Godaan Instan dan Pembiaran Sosial
Namun, menyalahkan pemerintah saja juga tidak adil. Kita, sebagai masyarakat, juga punya andil dalam suburnya praktik ini. Banyak yang tahu bahwa judi itu melanggar hukum dan bisa menghancurkan hidup namun tetap mencobanya karena satu hal yaitu harapan kosong untuk kaya mendadak.
Dapat kita saksikan secara langsung dengan mata kepala kita sendiri di beberapa tempat dan media contohnya di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, bahkan di ruang guru sekalipun, sering kita dengar kalimat seperti, "Ya siapa tahu hoki…" atau "Lumayan buat tambahan, asal jangan kecanduan." Kata-kata seperti ini menormalisasi pelanggaran. Lama-lama, kesalahan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi menjadi budaya dan Budaya jadi penyakit.
Apalagi bagi mereka yang hidup dalam tekanan ekonomi, judi terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Padahal kenyataannya, banyak yang justru semakin tenggelam dalam kemiskinan karena kalah taruhan. Kasus bunuh diri, perceraian, hingga pencurian kecil-kecilan karena judi online bukan lagi cerita baru. Ini kenyataan.
Dan yang lebih mencemaskan lagi, promosi judi kini sudah menyasar anak muda lewat influencer yang memamerkan "hasil menang" mereka, seolah-olah itu adalah cara cerdas untuk hidup mewah. Literasi digital dan pendidikan moral yang lemah menjadi celah paling mudah disusupi.
Kini yang kita pertanyakan adalah pemerintah Hadir atau Sekedar Pemadam Kebakaran?
Bila ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, tentu jawabannya tidak sederhana. Tapi kita bisa mulai dengan satu kenyataan negara belum cukup hadir. Bukan hanya dalam menindak, tapi juga dalam mencegah. Penindakan itu penting, tapi jika selalu bersifat reaktif, maka kita hanya sibuk memadamkan kebakaran tanpa pernah memeriksa sumber apinya.
Di sinilah seharusnya pemerintah tidak bekerja sendiri. Perlu sinergi antara Kominfo, Kemenag, Kemendikbud, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media sosial. Literasi digital harus diperkuat, pendekatan budaya diperbarui, dan pengawasan harus lebih canggih bukan sekadar memblokir, tapi juga mendeteksi dini lewat sistem berbasis kecerdasan buatan (AI).
Lebih penting lagi adanya edukasi. Kita tidak cukup hanya dengan bilang “judi itu haram” atau “judi itu ilegal”. Kita harus jelaskan mengapa, dan bagaimana bahayanya merambat diam-diam, menghancurkan nilai, keluarga, dan harapan masa depan.
Penutup dari saya adalah itu semua merupakan Sebuah Tanggung Jawab kita bersama. Judi online bukan hanya soal hukum yang dilanggar. Ini tentang sistem yang gagal, moral yang tergerus, dan harapan yang dijual murah oleh ilusi digital. Ia lahir dari celah kelembagaan, dibesarkan oleh pembiaran sosial, dan dibius oleh kebutuhan ekonomi.
Jika kita hanya menyalahkan pemerintah, kita abai. Tapi jika kita juga hanya menertawakan para penjudi tanpa melihat akar persoalan, kita pun ikut berdosa. Mengubahnya butuh waktu, strategi, dan kerja bersama. Kita butuh sistem yang lebih kuat, budaya digital yang sehat, dan masyarakat yang sadar bahwa tidak semua janji mudah itu nyata. Karena kalau dibiarkan, kelalaian hari ini akan menjadi kebiasaan besok pagi, dan dari kebiasaan itulah, lahir kehancuran yang kita tangisi terlalu terlambat. (*)
Fauzul Ikhsan Dafiq, mahasiswa UIN Bukittinggi